
Perempuan Desa: Penjaga Tradisi dan Jiwa Pertanian
Seorang ibu sedang memanen padi dengan sabar. Pemandangan ini mengingatkan saya pada sosok ibu saya sendiri, seorang petani desa yang tak pernah berhenti bekerja meski usianya semakin tua. Sebagai anak petani, saya tahu betul bagaimana bahagianya saat musim panen tiba—ada rasa lega dan syukur ketika jerih payah berbulan-bulan akhirnya berbuah hasil.
Namun, kebahagiaan itu sering kali tidak bertahan lama. Harga gabah yang jatuh di luar dugaan kerap meruntuhkan semangat, seolah permainan harga telah menjadi "ritual" tak terhindarkan di setiap musim panen. Kini, saya tidak lagi mengizinkan ibu saya bekerja terlalu berat. Usianya memang tidak muda, meski nalurinya sebagai petani tetap hidup. Selalu ada saja aktivitas yang dilakukannya di sawah atau di halaman rumah, seakan tubuhnya sudah menyatu dengan tanah dan padi.
Apa yang saya lihat pada ibu saya sebenarnya adalah potret banyak perempuan desa lain: mereka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan pertanian, bahkan ketika usia dan zaman terus berubah. Di tengah riuh mesin pemotong padi yang kian mendominasi hamparan sawah Nusantara, masih ada sudut-sudut desa yang setia menjaga kearifan lama dalam mengelola hasil bumi.
Pemandangan ini bukan sekadar soal menanam dan menuai, melainkan juga tentang ruang hidup perempuan desa—mereka yang diam-diam menjadi penopang utama tradisi agraris kita. Catatan penting: tulisan ini sama sekali tidak menafikan peran petani laki-laki. Di banyak desa, laki-laki dan perempuan saling bahu membahu menjaga sawah, mulai dari membajak, menanam, hingga panen. Namun, pengalaman pribadi saya menyaksikan seorang ibu memanen padi seorang diri di sawah tiba-tiba membawa ingatan pada sosok ibu kandung saya.
Dari situlah refleksi ini mengalir—sebuah potret kecil tentang ketekunan, kesabaran, dan daya tahan perempuan desa dalam menjaga tradisi panen padi.
Perempuan sebagai Penjaga Tradisi
Sejak fajar, perempuan desa sudah menyingsingkan lengan baju, mengikat kain di pinggang, dan menyiapkan diri untuk masuk ke petak sawah. Bagi mereka, panen bukan hanya rutinitas ekonomi, melainkan juga arena sosial, budaya, sekaligus spiritual. Dengan sabit padi, mereka memotong batang demi batang, lalu mengumpulkannya menjadi ikatan-ikatan kecil.
Proses ini berlanjut dengan cara merontokkan bulir padi secara sederhana: ikatan-ikatan itu disabetkan ke alat kayu atau bambu yang disusun khusus. Suara plak-plak terdengar berulang, bulir padi berhamburan jatuh, sementara bau gabah segar memenuhi udara. Gerakan ini memang kalah cepat dibanding mesin combine harvester, tetapi menyimpan makna. Setiap helai padi diperlakukan dengan hati-hati, seakan ada doa yang tersemat di dalamnya.
Di sela-sela aktivitas, terdengar canda dan tawa. Suara perempuan yang bersahutan menjadikan sawah bukan hanya tempat kerja, melainkan juga ruang interaksi sosial yang menguatkan solidaritas. Gotong royong, rasa kebersamaan, dan penghormatan pada bumi terjalin dalam setiap gerakan sederhana itu.
Dari Sawah ke Halaman Rumah: Pascapanen Tradisional
Setelah panen, halaman rumah berubah menjadi ruang produksi. Butiran padi dijemur di bawah terik matahari, dibalik dengan tampah atau gayung kecil agar kering merata. Menjemur padi bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga seni membaca tanda alam. Perempuan desa tahu kapan harus menutup jemuran dengan terpal karena mendung datang, atau kapan menambah waktu penjemuran agar kadar air berkurang sempurna.
Kejelian ini diwariskan turun-temurun tanpa buku panduan, tanpa catatan akademik, tetapi tetap teruji oleh waktu. Di masa lalu, padi kering disimpan di lumbung bambu yang menjulang di halaman. Saat panen raya, seluruh warga bahu-membahu menyimpan hasil bumi, menjadikannya pesta syukur kecil yang sarat makna. Kini, pemandangan itu semakin jarang terlihat.
Kebijakan Pertanian dan Ruang Perempuan yang Terpinggirkan
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar mendorong modernisasi pertanian melalui berbagai program: mekanisasi dengan mesin combine harvester, subsidi pupuk, hingga pengembangan food estate di sejumlah daerah. Kebijakan ini di atas kertas bertujuan mulia—meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Namun, di lapangan, kebijakan itu tidak selalu ramah bagi petani kecil, apalagi perempuan desa. Mekanisasi misalnya, memang mempercepat proses panen dan mengurangi kehilangan hasil. Tetapi biaya sewanya cukup tinggi bagi petani gurem yang hanya memiliki lahan 0,2-0,3 hektare. Di banyak desa, operator mesin combine datang dari luar daerah, sehingga nilai ekonomi tidak berputar di lingkar komunitas.
Perempuan yang dulu terlibat aktif dalam proses panen—dari menyabit hingga merontokkan padi—kehilangan peran sekaligus penghasilan tambahan. Program subsidi pupuk juga menghadirkan ironi. Data BPS menunjukkan lebih dari 70 persen petani Indonesia adalah petani kecil, namun mereka sering kali kesulitan mengakses pupuk subsidi karena keterbatasan kartu tani atau keterlambatan distribusi.
Akibatnya, perempuan desa yang biasanya mengatur ekonomi rumah tangga harus memutar otak lebih keras. Mereka menjadi "manajer krisis" di dapur, sekaligus tenaga tambahan di sawah ketika biaya produksi membengkak. Food estate, yang diproyeksikan sebagai lumbung pangan baru, juga menimbulkan tanda tanya. Model pertanian skala besar ini dikelola dengan pendekatan korporasi dan teknologi tinggi.
Pertanyaannya: di mana posisi petani kecil dan perempuan dalam skema besar itu? Jika lahan-lahan rakyat makin terpinggirkan, maka semakin sedikit ruang bagi kearifan lokal dan praktik tradisional yang diwariskan perempuan desa.
Modernisasi dan Pergeseran Peran
Tak bisa dipungkiri, kehadiran mesin pertanian mempercepat kerja. Combine harvester dapat menyelesaikan panen berhektar-hektar sawah hanya dalam hitungan jam. Tetapi, efisiensi itu datang dengan konsekuensi. Sabit padi tergantikan, gabah tak lagi dijemur, bahkan lumbung desa pun hilang satu per satu. Proses yang dulu menyatukan warga kini berubah menjadi sekadar pekerjaan mekanis yang dikerjakan operator mesin.
Akibatnya, peran perempuan dalam siklus pertanian kian menyusut. Mereka kehilangan ruang sosial yang dulu hadir dalam aktivitas bersama: menjemur padi sambil bercengkerama, menumbuk gabah sambil bertukar cerita, atau bergotong royong saat menyimpan hasil panen di lumbung. Modernisasi, di satu sisi, memang mengurangi beban fisik. Namun di sisi lain, ia juga memutus rantai kebersamaan yang menjadi inti kearifan lokal.
BPS mencatat, hampir 33 persen tenaga kerja pertanian di Indonesia adalah perempuan. Angka itu menunjukkan betapa besar kontribusi mereka. Sayangnya, kontribusi tersebut semakin tak terlihat di tengah mekanisasi yang serba cepat.
Tantangan Baru: Perubahan Iklim dan Panen Tradisional
Belakangan, perubahan iklim menjadi ujian baru bagi petani. Musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi. Bagi petani tradisional, terutama perempuan desa yang mengandalkan metode lama, situasi ini menambah lapisan kerumitan. Menjemur padi, misalnya, kini jauh lebih berisiko. Hujan bisa tiba-tiba turun di tengah hari, membuat gabah yang belum kering terancam rusak. Kadar air yang tidak stabil dapat menurunkan kualitas beras, bahkan memicu jamur.
Begitu pula dengan lumbung bambu tradisional yang rentan terhadap kelembaban udara tinggi. Fenomena global seperti El Nio dan La Nia pun berimbas langsung pada desa-desa kecil. FAO (Organisasi Pangan Dunia) bahkan menyebut perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi produksi pangan dunia. Di tengah kondisi itu, perempuan desa kembali memainkan peran penting: pengalaman panjang mereka membaca tanda-tanda alam—dari arah angin, gerak awan, hingga perilaku burung—menjadi pengetahuan tak tertulis yang membantu desa bertahan.
Menjaga yang Lama, Merangkul yang Baru
Kearifan lama dalam pertanian bukan berarti menolak teknologi. Justru tantangannya adalah bagaimana menemukan titik temu antara efisiensi modern dan nilai kebersamaan tradisional. Perempuan desa dapat tetap menjadi aktor penting, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai penjaga nilai. Pascapanen tradisional—dari merontokkan padi, menjemur, hingga menyimpan di lumbung—perlu didokumentasikan dan dirayakan sebagai bagian dari identitas budaya agraris kita.
Dengan begitu, anak cucu kelak tidak hanya mengenal beras dalam karung plastik dari supermarket, tetapi juga memahami perjalanan panjang bulir padi dari sawah hingga menjadi nasi di meja makan.
Perspektif Reflektif
Kisah panen tradisional yang dijalankan perempuan desa sesungguhnya lebih dari sekadar romantisme masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa pertanian memiliki wajah budaya dan kemanusiaan yang tak boleh hilang di balik jargon modernisasi. Jika kearifan lama ini punah, yang hilang bukan hanya alat sederhana seperti sabit atau lumbung bambu, melainkan juga nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa syukur yang menjadi inti dari kehidupan agraris.
Pertanyaannya: apakah kita rela melihat sawah hanya sebagai mesin produksi, tanpa lagi mendengar suara tawa perempuan desa di pematang, atau menyaksikan bulir padi dijemur di bawah matahari desa?
Menjaga keseimbangan antara teknologi dan tradisi, antara efisiensi dan kebersamaan, adalah tugas bersama. Sebab pada akhirnya, setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil perjalanan panjang yang tidak hanya melibatkan tanah dan air, tetapi juga tangan-tangan perempuan yang penuh kearifan.
Penutup
Cerita panen tradisional dengan sentuhan tangan perempuan desa mengingatkan kita bahwa pertanian bukan sekadar industri, melainkan juga kebudayaan. Di balik setiap bulir padi, ada jejak tangan, keringat, dan doa yang ditenun oleh perempuan. Jika modernisasi hanya dilihat dari sisi efisiensi, maka kita akan kehilangan lapisan makna yang lebih dalam: kebersamaan, rasa syukur, dan kearifan lama yang menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Selamat Hari Tani. Mari kita jaga bukan hanya sawah, tetapi juga suara dan tawa perempuan desa yang selama ini menjadi denyut nadi pertanian kita. Bangga menjadi anak petani.



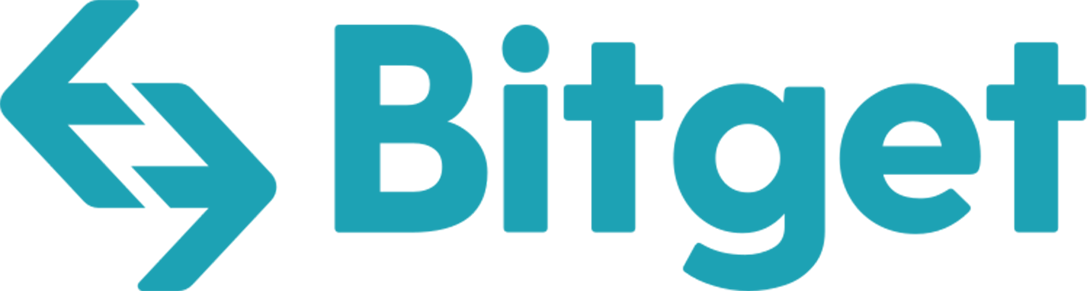










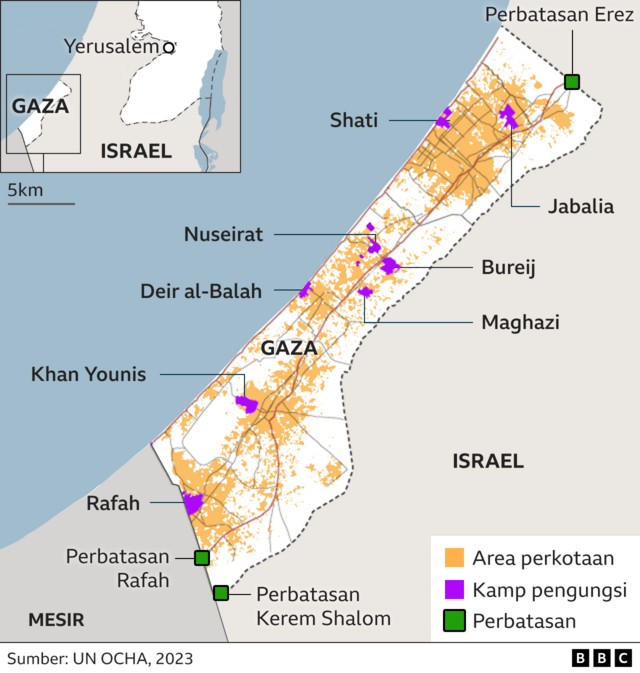


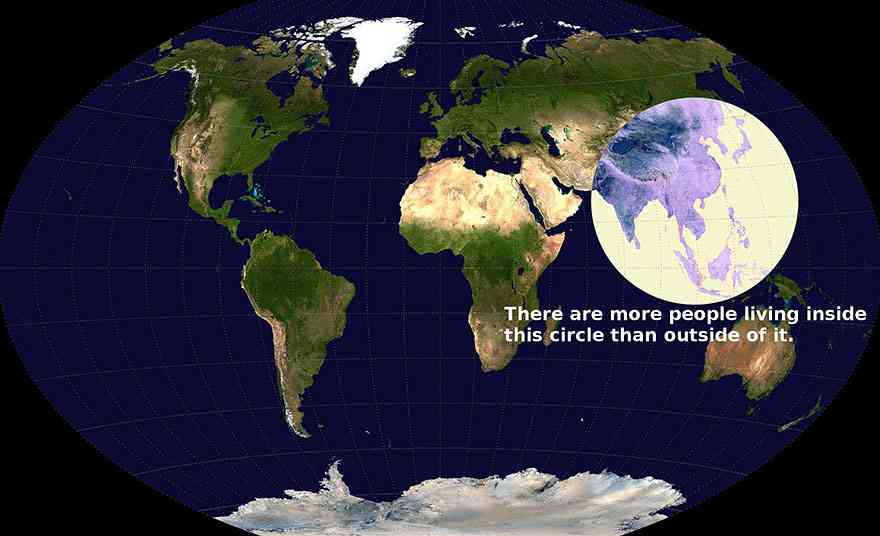




Komentar
Tuliskan Komentar Anda!