
Peran Pemerintah dan Bank Sentral dalam Ekonomi
Dalam dinamika perekonomian, peran pemerintah dan bank sentral sering kali dianggap sebagai dua entitas yang saling melengkapi. Pemerintah bertugas mengelola keuangan negara melalui kebijakan fiskal, sementara bank sentral, khususnya Bank Indonesia, mengendalikan moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun, dalam situasi kritis, norma ini sering kali terganggu, memicu munculnya konsep burden sharing.
Konsep Burden Sharing
Burden sharing adalah skema pembagian beban keuangan antara pemerintah dan bank sentral saat menghadapi krisis. Mekanisme utamanya melibatkan Bank Indonesia (BI) yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, kebijakan ini pertama kali diterapkan selama pandemi COVID-19, sebagai respons darurat terhadap krisis kesehatan dan ekonomi yang luar biasa.
Mekanisme Pelaksanaan
Pada masa pandemi, mekanisme burden sharing dirancang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pembelian SBN oleh BI dilakukan di pasar perdana, langsung dari pemerintah. Untuk membiayai belanja barang publik seperti sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, SBN diterbitkan dan dibeli langsung oleh BI dengan beban bunga nol persen. Sementara itu, untuk dukungan terhadap sektor bisnis, pemerintah menerbitkan SBN di pasar, dan beban bunga atas penerbitan ini dibagi rata 50:50 antara pemerintah dan BI.
Perkembangan Kebijakan
Setelah sempat dihentikan, kebijakan burden sharing kembali mengemuka di era pemerintahan baru. Rasionalisasinya bergeser dari "respons krisis" menjadi "pembiayaan pembangunan". Tujuannya adalah untuk mendukung program prioritas Asta Cita, seperti pembangunan 3 juta unit perumahan rakyat dan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Landasan Hukum
Landasan hukum bagi skema burden sharing yang diperbarui ini terletak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Undang-undang ini memungkinkan Bank Indonesia untuk membeli Surat Berharga Negara di pasar sekunder, walaupun pembelian di pasar perdana hanya dibolehkan dalam kondisi krisis.
Dukungan dan Kritik
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan dukungan ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang fiskal yang diperlukan pemerintah untuk membiayai program-program prioritasnya. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam. Kekhawatiran pertama adalah potensi inflasi yang bisa dipicu oleh skema tersebut. Ekonom Bhima Yudhistira berpendapat bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah bentuk "pencetakan uang".
Potensi Risiko
Kritik lain yang tak kalah serius adalah potensi terkikisnya independensi Bank Indonesia. Dengan menormalisasi burden sharing di luar situasi krisis, peran BI bergeser dari "pemberi pinjaman terakhir" menjadi "pembiaya pembangunan". Pergeseran ini berpotensi memicu fiscal dominance, di mana kebijakan moneter BI tidak lagi independen, melainkan menjadi alat untuk mencapai tujuan fiskal pemerintah.
Perbedaan dengan Quantitative Easing
Kadang, skema burden sharing di Indonesia disamakan dengan Quantitative Easing (QE) yang diterapkan oleh bank sentral global. Namun, ada perbedaan mendasar dalam konteksnya. QE umumnya digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter non-tradisional saat suku bunga sudah mendekati nol dan instrumen konvensional tidak lagi efektif.
Manfaat dan Tantangan
Meski mengundang perdebatan, tidak dapat dimungkiri bahwa burden sharing memiliki manfaat yang nyata. Kebijakan ini memberikan pemerintah sumber pembiayaan yang terukur dengan biaya rendah untuk program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Prinsip Implementasi
Sebagai instrumen kebijakan, burden sharing menawarkan dualitas yang kompleks. Ia terbukti efektif sebagai respons terhadap guncangan luar biasa, namun menjadi pedang bermata dua jika diterapkan di luar konteks krisis. Untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat, dibutuhkan komitmen kuat terhadap beberapa prinsip.
Pertama, perlu adanya batasan yang jelas dan terukur, baik dari segi nominal maupun waktu, untuk setiap intervensi BI. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan, dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana. Ketiga, pemerintah harus memiliki strategi keluar yang jelas, memastikan bahwa skema ini tidak menjadi mekanisme pembiayaan permanen yang dapat menimbulkan ketergantungan.
Selain itu, eksplorasi opsi pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), harus menjadi prioritas. Fondasi ekonomi yang kuat dibangun di atas kredibilitas dan disiplin.



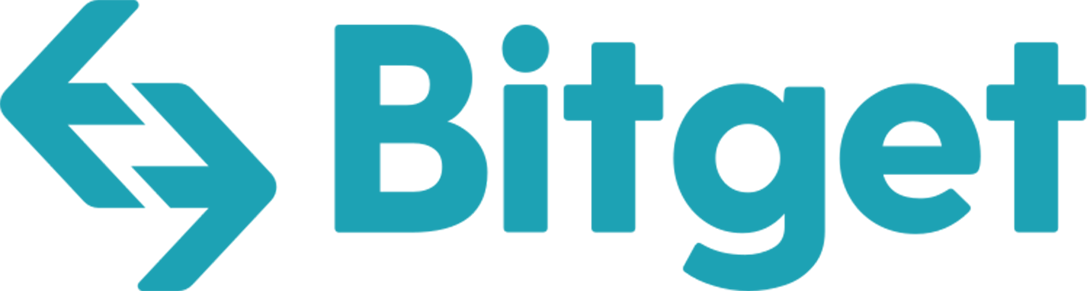











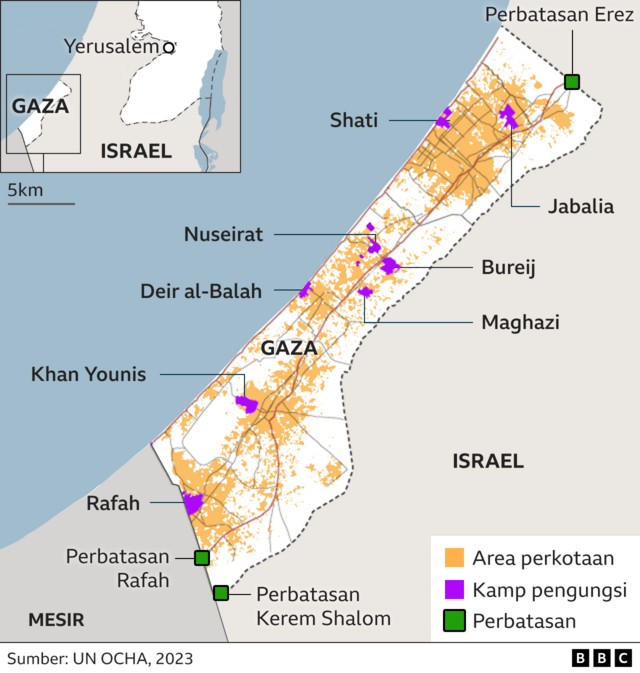






Komentar
Tuliskan Komentar Anda!