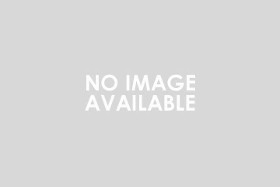
Proyek Hilirisasi dan Tantangan Sosial-Ekologis yang Terabaikan
Proyek hilirisasi sering kali dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di balik angka PDB yang meningkat dan pembangunan smelter, terdapat ongkos sosial-ekologis yang tidak pernah masuk dalam hitungan resmi. Negara sering kali terpaku pada statistik, seolah lupa bahwa manusia bukan sekadar angka. Kerja-kerja perawatan (care work) yang dipikul oleh perempuan lokal adalah salah satu contohnya. Mereka harus tetap melakukannya meski lingkungan tempat mereka hidup kian rusak dan terdistorsi.
Laporan dari Halmahera dan Konawe menunjukkan bahwa pencemaran akibat industri nikel menyebabkan kasus stunting, ISPA, hingga keracunan logam berat yang merusak kesehatan anak. Pada 2023 saja, tercatat 5.037 kasus stunting di Maluku Utara dan 499 kasus stunting di Halmahera Tengah. Kasus tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti air tidak layak minum, pencemaran udara, serta kurangnya asupan gizi.
Perempuan lokal sebagai pengasuh utama dalam keluarga, dipaksa menghadapi kondisi ini, nyaris tanpa dukungan dari negara. Dalam catatan UN Women, pekerjaan perawatan sering diabaikan dalam penghitungan ekonomi formal, namun melonjak drastis di tengah krisis. Ketika negara gagal menyediakan layanan dasar di kawasan tambang, perempuanlah yang harus menambal kekosongan infrastruktur melalui kerja-kerja perawatan yang makin berat, tidak dibayar, dan tidak diakui dalam sistem kebijakan.
Hilirisasi Bukan Solusi untuk Segala Persoalan
Hilirisasi tidak bisa menjadi solusi untuk semua masalah. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. Implementasi kesetaraan gender dalam tata kelola perusahaan menjadi penting, terutama dalam konteks proyek hilirisasi. Integrasi ekonomi perawatan dalam desain kebijakan adalah hal yang mendesak.
Kita perlu membongkar dikotomi antara ekonomi makro dan mikro, karena kebijakan makro bergantung pada kerja mikro yang dilakukan perempuan. Kebijakan makro yang nampak netral justru mengandung ketidakadilan gender dan sangat bergantung pada kerja perawatan yang tidak terlihat dalam sistem nasional.
Diane Elson menyebut kondisi ini sebagai “male bias”, yakni kecenderungan sistemik dalam teori, kebijakan, dan praktik pembangunan yang mengutamakan kepentingan laki-laki dan mengabaikan atau merugikan perempuan. Sistem ini mengkonstruksi ekonomi yang hanya mengedepankan produktivitas, pertumbuhan, dan kompetisi.
Model Ekonomi Makro yang Gender-Blind
Model ekonomi makro pun menjadi gender-blind—mengabaikan kerja perawatan sebagai penopang utama keberlangsungan ekonomi nasional. Dalam konteks hilirisasi, model kebijakan ekonomi tersebut mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan smelter alih-alih membangun posyandu, jalanan yang layak, ataupun sumur bersih bagi masyarakat lokal.
Situasi tersebut nyata terjadi di wilayah prioritas hilirisasi. Kerja-kerja perawatan seperti kerja reproduksi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari tidak diakui sebagai kerja ekonomi karena tidak mencetak output pasar. Akibatnya, pemerintah menggusur ruang hidup perempuan lokal dan menggantikannya dengan bangunan-bangunan penyokong industri nikel dalam rangka memuluskan agenda hilirisasi.
Perlu Revisi Paradigma Kebijakan
Dengan demikian, kita perlu menggeser paradigma kebijakan perekonomian formal. Kerja-kerja perawatan tidak boleh dilihat sebagai beban individual perempuan, tetapi sebagai infrastruktur penting bagi keberlangsungan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis. Diane Elson mengingatkan perlunya repositioning kerja perawatan dalam sistem perekonomian. Kerja perawatan harus diakui dan dimasukkan ke dalam kerangka analisis ekonomi yang sah, karena pengabaian terhadapnya bukan hanya tidak adil, tetapi juga merugikan secara struktural.
Untuk itu, diperlukan reposisi struktural yang mencakup tiga hal: mengakui, mengurangi, dan mendistribusikan ulang kerja-kerja perawatan yang selama ini dianggap “alami” dan tidak diperhitungkan secara ekonomi. Pemerintah perlu mengakui kerja ini sebagai bagian penting dari sistem ekonomi, mengurangi bebannya lewat penyediaan layanan publik memadai, serta mendistribusikan ulang tanggung jawabnya agar tidak dibebankan sepenuhnya kepada perempuan.
Reformasi Kebijakan Fiskal dan Pendekatan Holistik
Kebijakan fiskal Indonesia pun harus direformulasi. Gender-responsive budgeting perlu diterapkan dalam proyek hilirisasi. Indikator kerja tak berbayar harus diintegrasikan dalam sistem akuntansi nasional. Anggaran pun perlu berpihak pada infrastruktur sosial seperti sumber air bersih, klinik kesehatan dan posyandu, pendidikan, serta pengkondisian hunian layak bagi masyarakat terdampak.
Redistribusi juga dapat diwujudkan melalui pemberian cuti ayah, subsidi day care, serta jaminan sosial bagi kerja-kerja perawatan. Hilirisasi tidak perlu dibatalkan, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi kembali agar lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh fokus pada pembangunan smelter saja, namun juga perlu memprioritaskan infrastruktur perawatan yang menopang kehidupan sosial-ekologis perempuan lokal.
Tanpa pendekatan holistik yang responsif gender, hilirisasi hanya akan memperdalam ketimpangan dan memperpanjang ketergantungan ekonomi makro terhadap kerja-kerja perawatan. Sebaliknya, dengan menempatkan ekonomi perawatan sebagai fondasi kebijakan ekonomi formal, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain utama dalam agenda hijau global, tetapi juga menjadi negara yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.



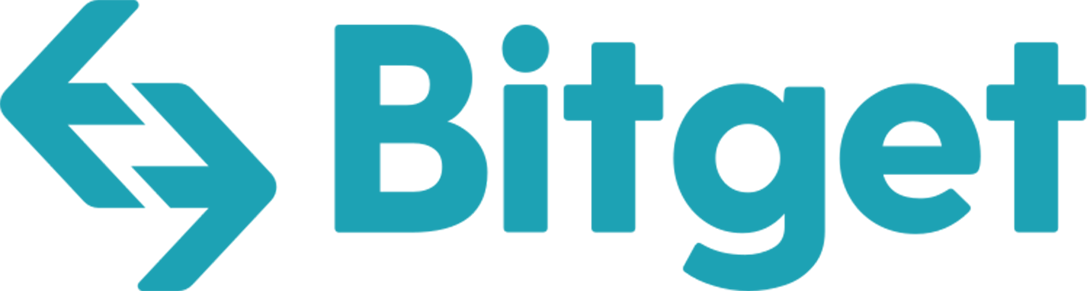




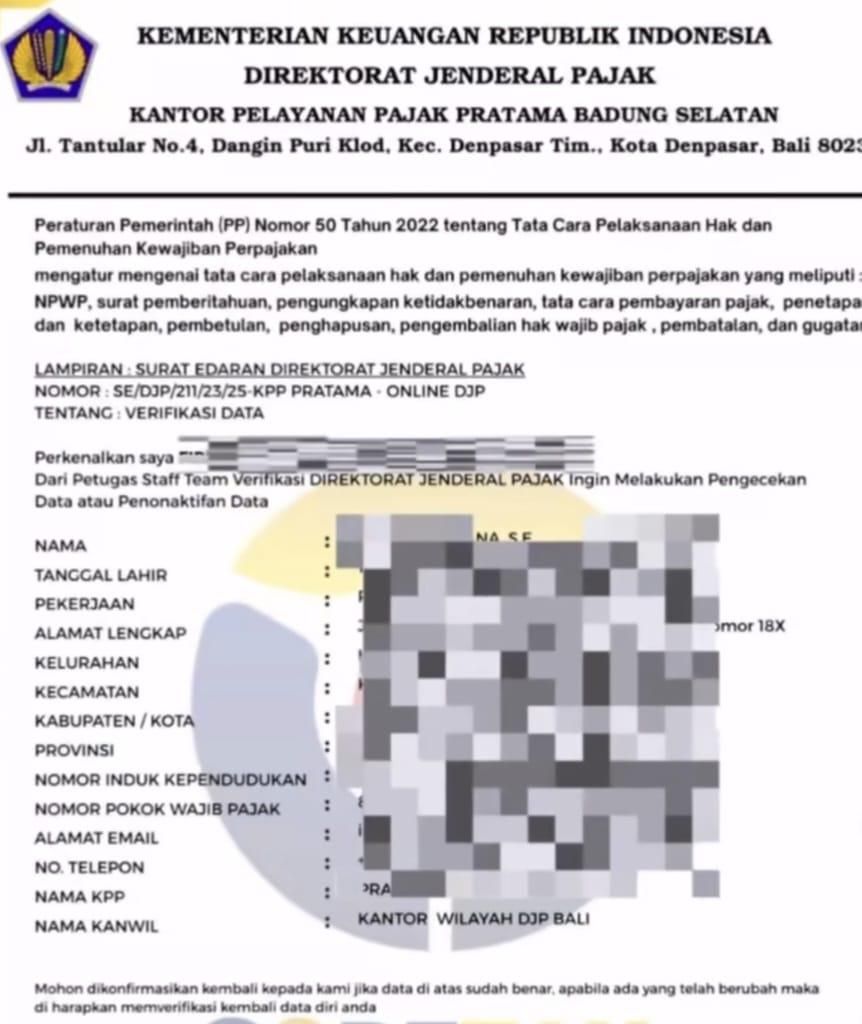







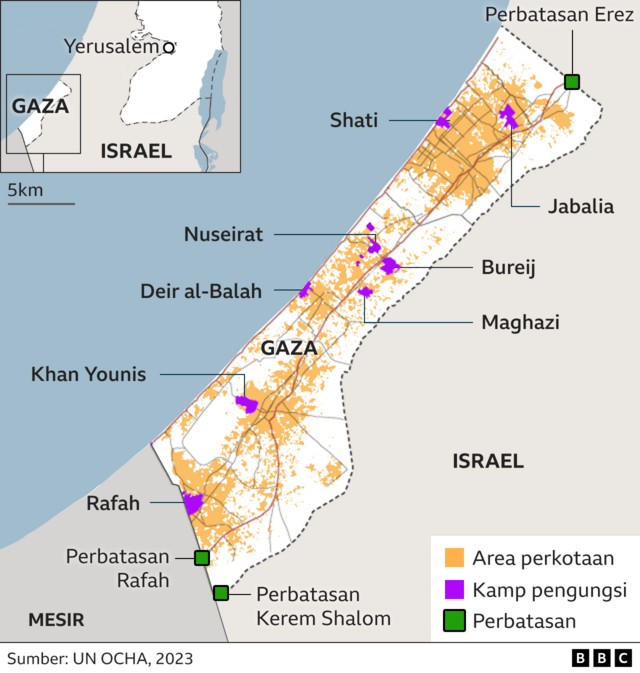





Komentar
Tuliskan Komentar Anda!