
Perencanaan IKN: Menjembatani Antara Ambisi dan Realitas
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern. Pemerintah menempatkan IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan, kota hijau berteknologi cerdas, serta representasi transformasi menuju negara maju. Secara politis, pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk mengurangi beban Jakarta yang telah lama menghadapi masalah kemacetan, banjir, polusi, dan kepadatan penduduk. Namun, pertanyaan yang lebih mendalam muncul: apakah IKN sekadar solusi teknokratis atas masalah Jakarta, atau justru sebuah eksperimen urbanisasi raksasa dengan risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami?
Sejarah perencanaan kota global memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia. Hall dan Tewdwr-Jones (2010) menekankan bahwa pembangunan kota baru hampir selalu menjadi arena tarik-menarik antara visi politik negara dan realitas ekonomi masyarakat. New towns di Inggris, misalnya, gagal berkembang bila tidak ditopang konektivitas regional yang kuat. Artinya, proyek seperti IKN tidak boleh hanya dipandang sebagai pemindahan gedung pemerintahan, melainkan sebagai proses pembentukan ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan baru yang harus berkelanjutan.
Johnson dan Fisher (1969) melalui kajian Urban Geography menunjukkan bahwa pertumbuhan kota di negara berkembang jarang terjadi karena daya tarik kota baru, melainkan karena tekanan dari pedesaan—kemiskinan, krisis agraria, serta minimnya peluang kerja. Dalam konteks IKN, hal ini berarti bahwa arus migrasi dari Jawa maupun daerah lain berpotensi menimbulkan masalah baru bila tidak diantisipasi dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perencanaan sosial yang matang. Kota baru tidak serta-merta akan tumbuh sehat hanya karena infrastruktur fisik megah tersedia.
Di sisi lain, ambisi pemerintah menjadikan IKN sebagai kota hijau yang berkelanjutan mengandung paradoks tersendiri. Berke dan Godschalk (2006) melalui Urban Land Use Planning memperkenalkan kerangka sustainability prism yang mencakup empat dimensi: lingkungan, ekonomi, keadilan sosial, dan livability. Jika salah satu dimensi diabaikan, hasil pembangunan cenderung timpang. Pertanyaannya: mampukah IKN menyeimbangkan perlindungan ekosistem hutan Kalimantan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi serta hak masyarakat adat?
Inspirasi lain datang dari gerakan Garden City yang diperkenalkan Ebenezer Howard pada awal abad ke-20. Buder (1990) dalam Visionaries and Planners mengulas bagaimana ide kota taman dimaksudkan untuk mengatasi masalah kota industri dengan menghadirkan ruang hijau dan komunitas egaliter. Namun, sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar kota taman gagal mempertahankan idealismenya, berubah menjadi suburbanisasi biasa yang eksklusif bagi kelas menengah. Situasi ini menjadi peringatan penting bagi IKN: konsep “forest city” yang diusung pemerintah bisa sekadar menjadi label indah jika tidak didukung institusi yang konsisten.
Dengan berangkat dari empat literatur penting ini, tulisan ini bermaksud melakukan rethinking terhadap pembangunan IKN. Evaluasi dilakukan tidak untuk menolak gagasan kota baru, tetapi untuk memastikan bahwa IKN tidak menjadi monumen politik belaka. Alih-alih, ia harus mampu tampil sebagai laboratorium urbanisme tropis abad ke-21: sebuah kota yang adil, hijau, inklusif, dan benar-benar kontekstual dengan realitas Kalimantan. Untuk itu, empat isu utama akan dibahas: migrasi dan urbanisasi, tata guna lahan dan keberlanjutan, inspirasi serta keterbatasan gerakan Garden City, dan integrasi regional.
Urbanisasi dan Migrasi
Urbanisasi adalah fenomena global yang selalu mengandung paradoks. Di satu sisi, kota dianggap sebagai pusat modernitas, inovasi, dan peluang. Di sisi lain, pertumbuhan kota sering kali didorong oleh krisis struktural di pedesaan. Johnson dan Fisher (1969) menjelaskan bahwa migrasi ke kota di negara berkembang biasanya lebih kuat dipicu oleh dorongan keluar dari desa—kemiskinan, stagnasi pertanian, terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan—daripada daya tarik intrinsik kota itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pembangunan kota baru seperti IKN tidak otomatis mengundang masyarakat dengan imajinasi tentang kesejahteraan, melainkan karena mereka ingin keluar dari jebakan kemiskinan di daerah asal.
Dalam konteks Indonesia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berpotensi memicu migrasi besar dari Jawa dan luar Kalimantan. Pemerintah berharap kehadiran IKN akan membuka lapangan kerja baru, tetapi sejarah urbanisasi menunjukkan adanya risiko lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru bila peluang ekonomi tidak sebanding dengan arus migran. Alih-alih menjadi motor pemerataan, IKN bisa berujung menciptakan segregasi sosial baru antara pekerja migran informal dengan kelas menengah birokrasi yang menjadi penghuni utama kota.
Kota-kota tropis raksasa di Asia telah memberikan banyak contoh tentang tantangan ini. Johnson menyoroti bahwa megacities di wilayah tropis cenderung menghadapi masalah transportasi, kesenjangan sosial, dan tekanan ekologis yang lebih kompleks dibanding kota kecil. Jakarta sendiri adalah contoh nyata: kota tumbuh cepat, tetapi infrastruktur dan pelayanan publik tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Jika pola serupa terjadi di IKN, pembangunan kota baru hanya akan memindahkan masalah urban Jakarta ke Kalimantan dengan skala berbeda.
Urbanisasi yang tidak terkendali juga dapat memunculkan fenomena sprawl atau pelebaran kota tanpa arah yang jelas. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian batas kota, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan akibat konversi lahan hutan yang masif. Dalam jangka panjang, sprawl mengurangi efisiensi tata kota dan menambah beban biaya transportasi. Bila IKN gagal mengendalikan pola migrasi dan permukiman, ambisi menjadikannya sebagai kota hijau akan berhadapan dengan realitas kawasan urban yang penuh tekanan ekologis.
Selain itu, migrasi besar ke IKN dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Kalimantan memiliki komunitas adat dengan hak historis atas tanah dan hutan. Kehadiran migran dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan ketegangan identitas, perebutan lahan, serta marginalisasi masyarakat asli. Pengalaman pembangunan kota baru di berbagai negara menunjukkan bahwa konflik antara pendatang dan komunitas lokal sering kali tak terhindarkan bila tidak ada mekanisme partisipasi dan perlindungan yang jelas.
Karena itu, perencanaan IKN harus menempatkan aspek migrasi sebagai agenda utama, bukan isu pinggiran. Perlu kebijakan ketat tentang penyediaan pekerjaan produktif, integrasi sosial, serta perumahan inklusif yang tidak hanya berfokus pada kelas menengah dan elite birokrasi. Tanpa strategi migrasi yang matang, IKN berisiko besar menjadi metropolitan tropis dengan masalah klasik: kemacetan, ketimpangan, dan polarisasi sosial-ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan kota baru harus dimulai dari pengakuan terhadap dinamika migrasi sebagai faktor penentu keberlanjutan, bukan sekadar tambahan teknis dalam perencanaan.
Keberlanjutan dan Tata Guna Lahan
Pemerintah sering menggaungkan bahwa IKN akan menjadi kota hijau dan berkelanjutan. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apa makna keberlanjutan dalam konteks pembangunan kota baru di Kalimantan? Berke dan Godschalk (2006) melalui Urban Land Use Planning memperkenalkan konsep sustainability prism yang mencakup empat dimensi: lingkungan, ekonomi, keadilan sosial, dan livability. Sebuah kota hanya bisa disebut berkelanjutan jika keempat dimensi itu seimbang. Jika salah satu sisi diabaikan, pembangunan akan melahirkan ketimpangan baru, baik secara ekologis maupun sosial.
Dalam konteks IKN, dimensi lingkungan menjadi sangat krusial. Kalimantan adalah paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, namun juga rentan terhadap deforestasi. Pembangunan kota di kawasan ini membawa risiko konversi hutan dalam skala besar, bahkan ketika pemerintah mengklaim bahwa IKN akan dibangun di lahan non-produktif. Pengalaman global menunjukkan bahwa pembangunan kota besar hampir selalu berdampak pada ekosistem di sekitarnya, baik melalui alih fungsi lahan, pencemaran, maupun fragmentasi habitat. Tanpa tata guna lahan yang ketat, klaim kota hijau bisa terjebak dalam praktik “greenwashing”.
Dimensi ekonomi juga tidak kalah penting. Kota baru membutuhkan basis ekonomi yang kokoh agar tidak hanya bergantung pada sektor pemerintahan. Jika IKN hanya menjadi pusat administrasi negara, tanpa didukung sektor produktif lokal, maka keberlanjutan ekonominya akan rapuh. Hal ini pernah terjadi pada sejumlah new towns di berbagai negara yang gagal tumbuh karena tidak mampu menarik investasi dan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Dalam jangka panjang, IKN bisa menjadi beban fiskal negara alih-alih motor pembangunan.
Aspek keadilan sosial menjadi tantangan lain yang harus diwaspadai. Kehadiran IKN berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat adat dan penduduk lokal yang memiliki ikatan historis dengan tanah dan hutan Kalimantan. Jika pembangunan hanya memprioritaskan birokrasi, investor, dan kelas menengah-atas, maka masyarakat lokal akan terpinggirkan. Keberlanjutan sejati, menurut Berke dan Godschalk, tidak bisa dilepaskan dari keadilan spasial: distribusi manfaat dan beban pembangunan harus adil bagi semua kelompok.
Dimensi terakhir adalah livability atau kelayakhunian. Kota yang berkelanjutan bukan hanya kota yang hijau secara visual, tetapi juga kota yang memberikan kualitas hidup yang baik: akses transportasi publik, ruang terbuka hijau, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan sosial yang inklusif. Jika hanya berfokus pada arsitektur megah dan simbol teknologi, IKN berisiko menjadi kota elitis yang tidak ramah bagi warganya sendiri. Dengan kata lain, keberlanjutan bukanlah jargon, melainkan pengalaman hidup sehari-hari yang nyata bagi masyarakat.
Dari perspektif tata guna lahan, keberlanjutan IKN menuntut perencanaan spasial yang berbasis ekologi tropis. Artinya, pembangunan harus benar-benar menghormati karakteristik lingkungan Kalimantan: iklim, topografi, dan sistem hidrologi. Tanpa itu, risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan degradasi tanah akan meningkat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan tata guna lahan tidak boleh dipandang sebagai aspek teknis tambahan, tetapi harus menjadi fondasi utama pembangunan IKN. Hanya dengan cara ini, cita-cita menjadikan IKN sebagai kota hijau dapat benar-benar terwujud.



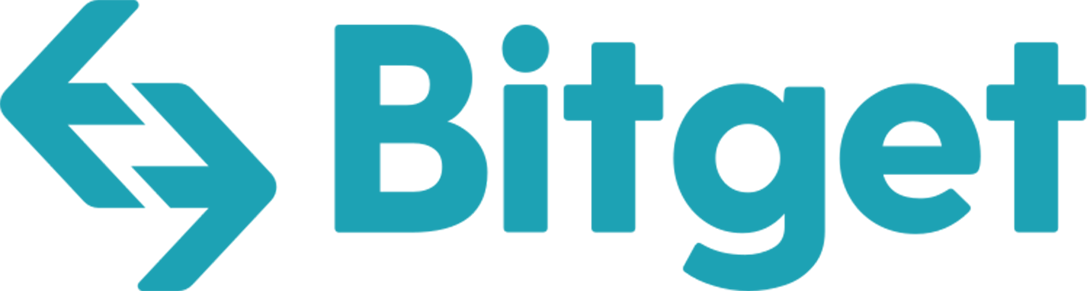











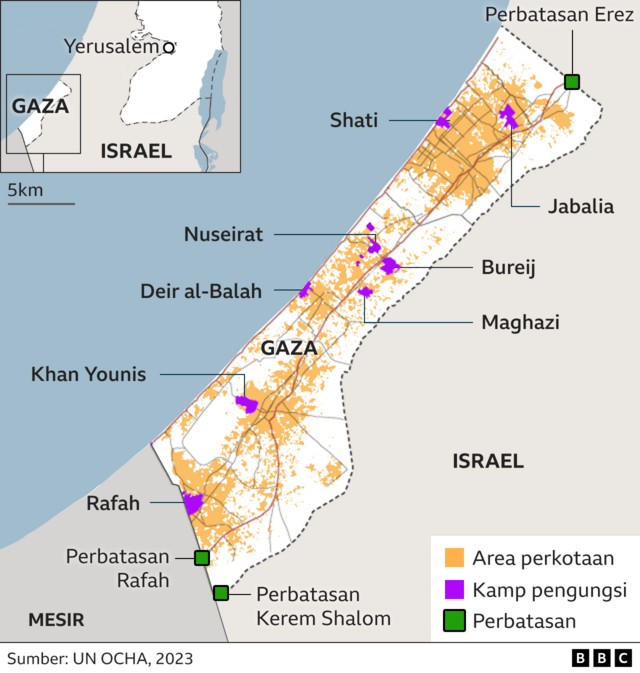






Komentar
Tuliskan Komentar Anda!